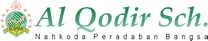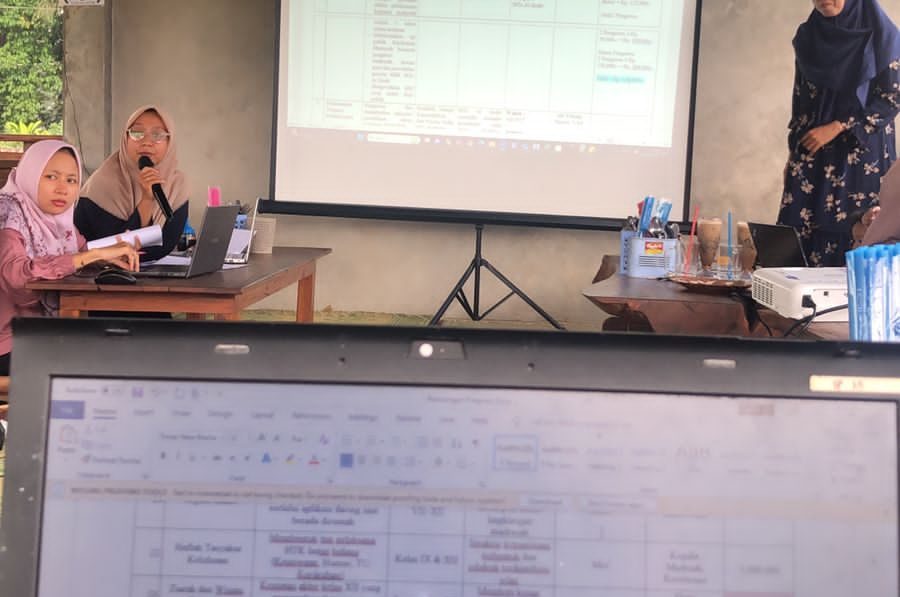Pendahuluan
Nasionalisme merupakan salah satu pilar utama dalam membangun negara-bangsa yang kuat dan berdaulat. Sebagai ideologi kebangsaan, nasionalisme tidak lahir secara instan, melainkan dibentuk melalui proses panjang yang melibatkan pendidikan, pengalaman sejarah, serta simbol-simbol nasional yang terus direproduksi secara kolektif. Dalam konteks Indonesia, sebuah negara yang majemuk secara etnis, agama, dan budaya, penguatan nasionalisme menjadi keniscayaan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Salah satu instrumen yang digunakan secara sistematis dalam membentuk kesadaran nasionalisme adalah upacara bendera, yang dilaksanakan secara rutin di sekolah-sekolah, instansi pemerintahan, dan lembaga negara.
Meskipun sering kali dianggap sebagai kegiatan administratif yang bersifat formalitas, upacara bendera sejatinya merupakan katalisator nasionalisme, yaitu sarana yang mempercepat dan memperkuat internalisasi nilai-nilai kebangsaan ke dalam kesadaran individu dan kolektif. Dengan menggabungkan elemen simbolik, edukatif, dan kultural, upacara bendera berperan penting dalam pembentukan karakter warga negara yang beridentitas nasional, berjiwa patriotik, dan memiliki loyalitas terhadap negara.
Konsep Nasionalisme dan Imagined Communities
Benedict Anderson (1983), dalam karya klasiknya Imagined Communities, menyatakan bahwa bangsa (nation) merupakan komunitas yang “dibayangkan” oleh anggota-anggotanya sebagai satu kesatuan politis dan emosional, meskipun mereka tidak saling mengenal secara langsung. Komunitas ini diciptakan melalui media simbolik seperti bendera, lagu kebangsaan, bahasa nasional, dan ritual kebangsaan, termasuk upacara bendera. Dalam perspektif ini, upacara bendera menjadi sarana untuk memperkuat ikatan imajiner antarwarga negara melalui pengalaman bersama dalam menyatakan rasa hormat terhadap simbol-simbol negara.
Pengibaran bendera Merah Putih, pengucapan Pancasila, menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya”, serta pembacaan UUD 1945 bukan hanya rutinitas teknis, melainkan tindakan simbolik yang mengandung nilai historis dan ideologis. Semua elemen tersebut merepresentasikan identitas, sejarah perjuangan, dan nilai-nilai yang menyatukan Indonesia sebagai sebuah bangsa. Dalam konteks ini, upacara bendera berfungsi sebagai ruang publik tempat identitas nasional direproduksi dan dikukuhkan secara berkala.

Dimensi Edukatif: Pendidikan Karakter dan Civic Culture
Selain aspek simbolik, upacara bendera memiliki fungsi edukatif yang sangat penting. Di lingkungan sekolah, kegiatan ini merupakan bagian dari strategi pendidikan karakter yang bertujuan menanamkan nilai-nilai seperti kedisiplinan, tanggung jawab, dan cinta tanah air. Kaelan (2013) menekankan bahwa Pancasila sebagai dasar negara harus diinternalisasi melalui proses pendidikan yang terstruktur, salah satunya melalui praktik-praktik simbolik yang berulang seperti upacara bendera. Nilai-nilai Pancasila tidak cukup diajarkan dalam bentuk teori, tetapi harus ditanamkan melalui pengalaman langsung yang membentuk habitus kebangsaan.
Wibowo (2012), dalam penelitiannya mengenai internalisasi nasionalisme di sekolah, menemukan bahwa siswa yang secara rutin mengikuti upacara bendera memiliki tingkat kesadaran kebangsaan yang lebih tinggi dibandingkan siswa yang tidak mengikuti kegiatan tersebut secara konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan upacara bendera sebagai kegiatan rutin memiliki dampak positif terhadap pembentukan civic culture di kalangan pelajar.
Lebih lanjut, Tilaar (2002) menyatakan bahwa pendidikan tidak boleh dipisahkan dari konteks sosial dan politik masyarakat. Ia harus menjadi alat transformasi sosial yang memperkuat integrasi nasional. Dalam hal ini, upacara bendera bukan hanya bentuk pendidikan formal, tetapi juga merupakan bentuk pendidikan kewarganegaraan non-formal yang memainkan peran dalam pembentukan warga negara yang aktif dan bertanggung jawab.
Relevansi dalam Konteks Globalisasi dan Social Distruption
Tantangan terbesar dalam penguatan nasionalisme saat ini adalah globalisasi dan digitalisasi, yang telah menggeser orientasi nilai masyarakat (Social Distruption) dari yang berbasis kolektif menuju individualistik. Arus informasi yang cepat, eksistensi media sosial, serta penetrasi budaya asing dapat menyebabkan terjadinya erosi nilai-nilai nasionalisme, terutama di kalangan generasi muda. Dalam konteks ini, keberadaan upacara bendera menjadi semakin penting sebagai penyeimbang terhadap pengaruh eksternal yang dapat menggerus identitas masyarakat.
Sayangnya, seperti yang dikritik oleh Darmaningtyas (2004), sering kali praktik-praktik simbolik dalam pendidikan nasional hanya dijalankan secara formalitas tanpa makna yang mendalam. Upacara bendera tidak dihayati, melainkan hanya dijalani sebagai kewajiban administratif. Ini menyebabkan nilai-nilai yang ingin disampaikan melalui kegiatan tersebut tidak tertanam secara substantif.
Untuk itu, diperlukan reinterpretasi dan revitalisasi upacara bendera agar tetap relevan dan bermakna. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (2017) melalui program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) telah menekankan bahwa kegiatan rutin seperti upacara bendera harus dijadikan sebagai sarana reflektif untuk membentuk karakter bangsa, bukan sekadar kegiatan protokoler. Misalnya, amanat pembina upacara dapat dikembangkan menjadi media penyampaian nilai-nilai toleransi, persatuan dalam keberagaman, pentingnya bela negara, dan semangat gotong royong dalam konteks kekinian.
Urgensi Kebijakan dan Penguatan Institusional
Penting untuk dicatat bahwa eksistensi upacara bendera sebagai media pendidikan nasionalisme telah mendapat legitimasi dalam regulasi formal. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Undang-Undang Republik Indonesia, 2003).
Dalam implementasinya, institusi pendidikan memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan bahwa upacara bendera dijalankan tidak hanya sebagai ritual, tetapi sebagai bagian dari proses pembentukan warga negara yang utuh. Hal ini membutuhkan kolaborasi antara pendidik, kepala sekolah, dan pemangku kebijakan untuk menciptakan suasana upacara yang edukatif, inspiratif, dan kontekstual dengan dinamika sosial-politik yang sedang berkembang.
Kesimpulan
Upacara bendera merupakan simbol kebangsaan yang kaya akan makna historis, ideologis, dan edukatif. Dalam perspektif nasionalisme modern, ia bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi merupakan mekanisme penting dalam membentuk kesadaran kolektif, loyalitas terhadap negara, serta identitas nasional. Sebagai katalisator nasionalisme, upacara bendera mempercepat proses internalisasi nilai-nilai kebangsaan melalui pengalaman simbolik yang berulang dan bermakna.
Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan dan pemaknaannya. Tanpa pengelolaan yang baik dan pendekatan yang kontekstual, upacara bendera berisiko menjadi kegiatan simbolik yang kehilangan makna substantif. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk merevitalisasi praktik ini, menjadikannya sebagai sarana reflektif dan transformatif dalam membangun bangsa yang berkarakter, berdaulat, dan bermartabat.

Daftar Pustaka
Anderson, B. (1983). Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism. Verso.
Darmaningtyas. (2004). Pendidikan yang memiskinkan. Galang Press.
Kaelan. (2013). Pendidikan Pancasila. Paradigma.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2017). Modul pendidikan penguatan karakter (PPK). Kemendikbud.
Tilaar, H. A. R. (2002). Pendidikan, kebudayaan, dan masyarakat madani Indonesia. Grasindo.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Wibowo, A. (2012). Internalisasi nilai-nilai nasionalisme melalui kegiatan upacara bendera di sekolah. Jurnal Pendidikan Karakter, 2(1), 34–42.